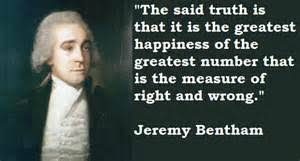Atip Latiful Hayat
Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filosof dan ahli hukum Inggris yang dijuluki sebagai “Luther of the Legal World” (Luther dalam dunia hukum). Julukan ini meminjam ketokohan teolog Martin Luther yang melakukan reformasi terhadap doktrin-doktrin tertentu dalam ajaran Katolik. Bentham dianggap sebagai figur yang melakukan reformasi sistem hukum Inggris pada abad ke-18 yang dianggap ketinggalan zaman, dan bahkan cenderung korup. Bentham memberikan kritik tajam sekaligus tawaran reformasi terhadap sistem hukum Inggris. Utilitarianisme adalah tawaran Bentham untuk mendesain ulang sistem hukum Inggirs yang dinilainya dekaden.
Utilitarianisme dikenal juga sebagai konsekuensialisme. Menurut pakar sejarah, adalah Richard Cumberland, seorang filosof moral Inggris abad ke 17 yang dianggap sebagai orang pertama yang menggagas paham utilitarianisme. Kemudian Francis Hutcheson memberikan sentuhan teori yang lebih jelas mengenai paham ini. Dia bukan hanya menganalisis bahwa perbuatan yang baik itu adalah yang memberikan manfaat kepada banyak orang (the greatest happiness for the greatest numbers), tapi juga mengusulkan apa yang ia sebut sebagai “moral arithmetic” untuk mengkalkulasinya. Pengembangan teori ini selanjutnya dilakukan oleh David Hume, filosof dan sejarawan Skotlandia. Namun, Bentham dianggap sebagai figur yang secara utuh dan komprehensif mampu memformulasikan dan kemudian mempopulerkan paham utililitarianisme.[1] Meskipun demikian, Bentham sendiri mengakui bahwa teorinya itu merupakan ramuan dari pemikiran pakar dan filosof sebelumnya seperti Joseph Priestly, Claude Adrien Helvetius, Cesare Beccaria, dan tentu saja David Hume.
Menurut ajaran utilitarianisme, suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan ketidaksenangan. Bukan saja kebahagiaan bagi para pelakunya, tapi juga kebahagiaan bagi orang lain. Utilitarianisme merupakan oposisi bagi egoisme yang berpendirian bahwa seseorang harus memenuhi kepentingannya sendiri, meskipun hal tersebut diperoleh dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Utilitarianisme juga berbeda dengan teori etika yang menetapkan bahwa suatu perbuatan di nilai baik atau buruk didasarkan atas motivasi pelakunya, sedangkan utilitarianisme menekankan kepada kemanfaatannya. Bagi utilitarianisme, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang baik lahir dari motivasi yang jelek. Paham utilitarianisme menekankan kepada perbuatan bukan kepada individu pelakunya. Singkat kata, ajaran pokok dari utilitarianisme adalah prinsip kemanfaatan (the principle of utility).
- Sketsa Biografis
Jeremy Bentham lahir pada tanggal 15 Pebruari 1748 di Houndsditch, London. Bentham dikenal sebagai “anak ajaib” (child prodigy), karena semasa balita dia seringkali ditemukan berada di ruang kerja ayahnya sedang membaca berjilid-jilid buku mengenai sejarah Inggris. Dia sudah mulai belajar bahasa Latin pada usia 3 tahun. Ibunya meninggal dunia ketika Bentham berusia 11 tahun, satu tahun sebelum dia bersekolah di Queen College Oxford.[2] Kecerdasaan Bentham mulai nampak antara lain melalui perkenalannya dengan buku ‘Logic’ karya Robert Sunderland. Setelah lulus, pada November tahun 1763, ia melanjutkan studi hukum di Lincoln’s Inn dimana ia mengikuti dengan penuh gairah kuliah-kuliah dari para pakar hukum kenamaan pada waktu itu semisal Lord Mansfield.[3]
Namun, Bentham kemudian merasa kecewa dengan hukum, khususnya setelah mendengar kuliah hukum dari figur ahli hukum otoritatif pada masa itu yaitu Sir William Blackstone (1723-1780). Setelah lulus dari Loncoln’s Inn, alih-alih menjadi praktisi hukum sebagaimana dicita-citakan ayahnya, Bentham akhirnya memutuskan menjadi seorang teoritisi hukum. Keputusan ini sangat mengecewakan ayahnya yang berharap Bentham menjadi seorang praktisi hukum.[4] Sepanjang hidupnya, Bentham berhidmat untuk ilmu pengetahuan dengan menghasilkan karya-karya tulis berbobot yang penuh kritik terhadap sistem hukum yang berlaku saat itu sekaligus menawarkan perbaikan-perbaikannya. Bentham terus berkarya, bahkan ketika usianya sudah menginjak 80 tahun.[5]
Pada tahun 1788 Bentham berhasil menyelesaikan karya besarnya yang kelak menjadi magnum opus-nya yaitu “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, yang diterbitkan pada tahun 1789. Dalam buku ini, Bentham menguraikan pemikirannya yang terkenal yaitu utilitarianisme. Ketenaran karya ini menyebar secara luas dan cepat. Bentham mendapatkan kewarganegaraan Prancis pada tahun 1792. Pemikiran dan nasihat-nasihat hukumnya diterima dengan penuh hormat di negara-negara Eropa dan Amerika. Pada tahun 1823, Bentham membantu pendirian Westminster Review (1824), jurnal utilitarian pertama yang dimaksudkan untuk menyebarkan prinsip-prinsip radikalisme filosofis dan juga pendirian University College, London.[6]
Bentham meninggal pada 6 Juni 1932 di Queen Square dalam usia 85 tahun. Sesuai dengan wasiatnya, tubuhnya dibedah di hadapan rekan-rekannya. Kemudian, kerangkanya dikonstruksi dengan dipenuhi lilin dan pakaiannya dikenakan pada kerangka tersebut. Patung Bentham tersebut disimpan di University College, London. Warisan Bentham untuk dunia hukum antara lain: Fragment on Government (1776); Defence of Usury (1787); Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789); Traite de Legislation Civile et Penale (1802); Pusnishment and Rewards (1811); Parliamentary Reform Cathecism (1817); The Influence of Natural Religion upon the Temporal Happiness of Mankind (1822); Treatise on Judicial Evidence (1825).
- Utilitarianisme
Utilitarianisme termasuk yang digagas Bentham adalah bagian dari sistem etika. Secara garis besar, sistem etika terbagi menjadi 2 yaitu teleologis (berorientasi pada tujuan) dan deontologi (berorientasi kepada kewajiban. Deon : apa yang harus dilakukan.) Dalam sistem teleologis, baik tidaknya suatu perbuatan diukur berdasarkan konsekuensinya. Karena itu, sistem ini disebut juga sebagai konsekuensialisme yang salah satu alirannya adalah utilitarianisme. Dalam utilitarianisme, tujuan perbuatan adalah memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang. Sementara itu, deontologi adalah sistem etika yang tidak mengukur baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Sistem ini tidak memfokuskan kepada tujuan dari suau perbuatan, melainkan semata-mata wajib tidaknya perbuatan tersebut dilakukan.
Pada masa Bentham, meskipun feodalisme sudah terkubur, namun hirarki sosial masih tetap berjalan dalam wujud perbedaan kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah (buruh). Nasib masyarakat kelas bawah tentu saja sangat memilukan. Akses kepada peradilan yang adil tertutup, karena peradilan bisa di beli. Buruh dieksploitasi nyaris tanpa batasan dan perlindungan, karena absennya hukum perburuhan. Merespon situasi sosial yang secara moral dekaden, Bentham mengajukan sistem moral baru yang diyakininya dapat mengembalikan kepada sistem sosial yang adil. Bentham mengajukan proposisi sebagai berikut; yang baik (good) adalah yang menyenangkan atau membahagiakan (pleasure) dan yang buruk (bad) adalah yang menyakitkan (pain). Bentham menjadikan hedonisme (pencarian kesenangan) sebagai basis teori moralnya yang kelak lebih dikenal sebagai hedonistic utilitarianism. Nilai utama adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai intrinsik, sedangkan sarana untuk mencapainya merupakan nilai-nilai instrumental. Secara demikian, maka kesenangan memiliki dua nilai yaitu instrinsik dan instrumental. [7]
Menurut Bentham, secara alamiah manusia hidup dalam pusaran dua kekuatan yaitu ketidaksenangan (pain) dan kesenangan (pleasure). Selengkapnya Bentham mengatakan sebagai berikut: “Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects, are fastened to their throne”.[8] Dalam konteks ini, kebahagiaan akan dipahami sebagai keadaan yang sepenuhnya berada dalam kesenangan dan bebas dari kesusahan. Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai hal yang baik atau buruk sepanjang dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan seseorang. Inilah yang merupakan konsep dasar dari teori utilitarianisme Bentham (the princile of utility).
Bentham memaknai kegunaan atau kemanfaatan (utility) sebagai sesuatu yang dimiliki yang dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan dan ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan ini ada pada tingkat individu yang menghasilkan kebahagiaan individual (happiness of individual) maupun masyarakat (happiness of community).[9] Bagi Bentham, moralitas suatu perbuatan ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan segenap manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dianut oleh hedonisme klasik. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasik Bentham mengenai kebahagiaan : the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas).[10]
Kualitas kesenangan atau kebahagiaan selalu sama, yang mungkin berbeda adalah kuantitasnya. Oleh karenanya, menurut Bentham, prinsip utilitarianisme ini harus diukur secara kuantitatif.[11] Konsekuensinya, bukan hanya the greatest number yang dapat dikalkulasi, juga the greatest happiness. Dengan alasan ini Bentham kemudian mengembangkan apa yang disebutnya sebagai the hedonistic atau felicific calculus (kalkulus kesenangan). Bentham kemudian merinci faktor-faktor yang menentukan tingkat kesenangan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu: intensitas (intensity), waktu (duration), kepastian (certainty), dan kedekatan (propinquity) dari perasaan senang atau sedih.[12] Misalnya, adanya kepastian tentang sesuatu yang akan anda peroleh baik jabatan maupun perolehan materi, maka akan semakin banyak kesenangan dan kepuasaan yang akan anda dapatkan ketika memikirkannya. Begitu juga semakin dekat perolehan jabatan atau materi tersebut, maka semakin bertambah pula kesenangan yang anda rasakan. Sebaliknya, semakin tidak pasti semakin menjauh pula rasa bahagia pada diri anda. Selanjutnya suatu kesenangan akan memproduksi kesenangan-kesenangan lainnya (fecundity). Demikian pula, kesenangan dan kepedihan kita akan dapat mempengaruhi kesenangan dan kepedihan orang lain (extent).[13] Misalnya, seorang guru akan merasa senang ketika anak didiknya berprestasi dan seorang orang tua akan sangat sedih mendapati anaknya sakit.
Dengan kalkulus kesenangan akan diketahui apakah akan menghasilkan saldo positif atau negatif. Jika suatu perbuatan menghasilkan lebih banyak kesenangan daripada ketidaksenangan, maka akan menghasilkan saldo positif dan perbuatan tersebut akan dinilai secara moral sebgai perbuatan baik. Namun, kalkulasi ini hanya dapat diterapkan untuk membandingkan di antara perbuatan-perbuatan sejenis, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak sejenis tidak mudah menerapkannya. Misalnya, membandingkan kenikmatan olah raga dan kenikmatan beribadah. Kalkulus kesenangan dapat digunakan untuk mengukur perbuatan-perbuatan yang tidak masuk dalam kategori keutamaan atau kerendahan, misalnya adat kebiasaan. Jika suatu perbuatan terbukti memberikan kenikmatan untuk banyak orang, maka perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan baik, meskipun orang lain mengatakan buruk. Sebaliknya, jika terbukti mendatangkan lebih banyak kesusahan, maka dianggap sebagai perbuatan buruk, meskipun orang lain mengatakan baik. Inilah esensi Utilitarianisme.
Dalam perkembangannya, utilitarianisme Bentham menginspirasi dan bahkan menjadi fondasi bagi suatu gerakan perubahan yang kemudian terkenal dengan sebutan “philosophical radicalism,” yang menguji dan mengevaluasi seluruh institusi dan kebijakan dengan menerapkan prinsip kemanfaatan (the principle of utility). Pemikiran Bentham menarik banyak pemikir muda pada permulaan abad ke 19 untuk bergabung yang akhirnya menjadi “murid” nya seperti David Ricardo yang memberikan bentuk klasik kepada ilmu ekonomi, James Mill (ayah dari John Stuart Mill), dan John Austin (teoritisi hukum). James Mill mengadvokasi perlunya pemerintahan berbasis perwakilan dan hak pilih bagi perempuan yang didasarkan atas teori utilitarianisme. Mill dan pengikut Bentham lainnya juga mendorong adanya reformasi parlemen di Inggris pada awal abad ke 19. Atas dasar utilitarianisme pula John Stuart Mill mendorong kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Dia juga menolak adanya intervensi pemerintah dan masyarakat terhadap kebebasan individu yang tidak membahayakan orang lain.[14]
Menurut Bentham, proposisi “the greatest happiness of the greatest number” akan berperan utamanya dalam proses legislasi, dimana para legislator akan berusaha untuk menciptakan kebahagiaan yang optimal bagi seluruh masyarakat dengan jalan menciptakan identitas kepentingan antar anggota masyarakat. Contohnya, dengan menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan, pembuat hukum ingin menjadikan pelakunya tidak membahayakan orang lain. Karya yang berjudul An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) yang sekaligus merupakan karya masterpiece Bentham sebenarnya didesain sebagai pengantar dalam penyusunan kitab undang-undang hukum pidana (…that of serving as an introduction to a penal code).[15]
Utilitarianisme Bentham pada gilirannya akan menawarkan konsep baru mengenai fungsi dan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut.[16] Dalam perspektif utilitarianisme, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan disini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (happiness). Dalam konteks ini yang ditekankan bukan adil atau tidaknya suatu hukum, melainkan sampai sejauhmana hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.[17] Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka hukum harus mencapai empat tujuan, yaitu memberi sumber nafkah hidup (subsistence), kecukupan (abundance), keamanan (security), dan kesetaraan (equality).
- Utilitarianisme dan Keadilan
Utilitarianisme sebagai teori etika politik dan teori hukum hakikatnya merupakan produk dari pola pikir masyarakat Inggris yang pada umumnya selalu dinisbahkan kepada Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarianisme menyakini bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu termotivasi dalam hidupnya untuk mendapatkan kebahagiaan dan menjauhi ketidaksenangan dan kebahagiaan individual itu melibatkan individu lainnya yang untuk melakukannya memerlukan pengaturan. Secara demikian, utilitarianisme sangat erat kaitannya dengan etika praktis dan juga politik praktis. Tujuan hukum adalah untuk mencapai dan menjamin kebahagiaan bagi masyarakat (the greatest happiness of the greatest number). Menurut utilitarianisme, kriteria baik dan buruk yang harus ada di dalam hukum ada di dalam kebahagiaan itu sendiri. Semua institusi politik dan publik harus dinilai berdasarkan apa yang dikerjakannya bukan oleh ide-idenya, yaitu sampai sejauhmana mreka memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, bukan karena kesesuaiannya dengan hak-hak alamiahnya atau keadilan yang mutlak. Utilitarianisme didasarkan kepada doktrin hedonisme yang memandang bahwa manusia adalah makhluk yang berkesadaran, makhluk yang memiliki perasaan dan sensitivitas. Prinsip kemanfaatan ditujukan untuk menguji dan mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Negara, menurut utilitarianisme harus merealisasikan kebahagiaan sebanyak-banyakny bagi masyarakat dan ini merupakan alat, bukan tujuan.
Bentham tidak mengakui hak asasi individu dan oleh karenanya dia menempatkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan (a subordinate aspect of utility).[18] Dalam suatu undang-undang, keadilan merupakan bagian implisit dari kemanfaatan. Oleh karena itu, bagi Bentham, keadilan adalah sesuatu yang ditetapkan di dalam undang-undang. Bentham tidak mengakui keadilan sebagai hak asasi manusia baik secara umum maupun khusus, karena dia tidak mengakui adanya hak-hak alamiah (natural rights). Dalam karyanya, “Anarchical Fallacies”, Bentham mengkritik Deklarasi Perancis mengenai hak asasi manusia dan menganggapnya hanya sebagai retorika kosong. Oleh karena itu Bentham menekankan agar undang-undang mencerminkan kebahagian masyarakat yang berbentuk keamanan (security), nafkah hidup (subsistence), kecukupan (abundance), dan kesetaraan (equality).
Berbeda dengan Bentham, John Stuart Mill berpendapat bahwa meskipun standar keadilan itu harus didasarkan kepada nilai kemanfaatannya, namun esensi keadilan itu harus berasal dari dua perasaan yaitu dorongan mempertahankan diri dan perasaan simpati.[19] Rasa keadilan juga dimaksudkan sebagai imbalan atau bahkan balasan atas tindakan kejahatan.[20] Hasrat membela korban kejahatan, bukan hanya didasarkan kepada alasan personal, tapi juga karena perbuatan tersebut menyakiti anggota masyarakat lainnya dan kita bersimpati kepadanya sekaligus merasakan seandainya hal serupa menimpa diri kita. Keadilan ini, menurut Mill, mencakup semua prasyarat moral yang diperlukan dalam kehidupan yang dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan merupakan sebuah kewajiban.[21]
Selain perbedaan sebagaimana disebutkan di atas, pendirian Bentham mengenai keadilan sebagai subordinat dari kemanfaatan dibuktikan dengan fakta bahwa dia menentang luasnya diskresi yang diberikan kepada hakim untuk menafsirkan hukum. Bentham menyarankan agar interpretasi hakim tidak boleh melebihi dari pemahaman yang ada dalam undang-undang. Aktivitas interpretasi tersebut tidak boleh menyingkirkan makna yang diinginkan oleh undang-undang. Singkat kata, tidak boleh penafsiran hakim menggantikan makna yang dimaksudkan oleh undang-undang.[22] Bentham menganggap hakim yang seperti ini ibarat seorang tukang obat yang memberikan kepada penonton ramuan yang manis dan pahit yang diambil dari gelas yang sama.[23] Selanjutnya Bentham melancarkan kritik pedasnya terhadap “judicial activism” sebagai berikut:
The serpent, it is said can pass his whole body whenever he can introduce his head. As respects legal tyranny, it is this subtle head of which we must take care; least presently we see it followed by all the tortious fields of abuse.[24]
Benthamisme mengkritik para hakim sebagai perampas kuasa ketika mereka mengganti maksud para pembuat undang-undang dengan tafsiran mereka sendiri dan tafsiran hakim itu dianggapnya sebagai tafsiran yang arbitrer.[25]
Kritik Bentham terhadap hakim itu tidak hanya terbatas karena mereka merampas kuasa pembuat undang-undang, dia juga mengkritik sebagian hakim yang melakukan apa yang dia sebut sebagai “..the delay and denial of justice”. Bentham secara sarkastis menjuluki mereka sebagai “Judges and Co.”[26] Oleh karena itu, meskipun Bentham tidak memformulasikan secara komprehensif teori dan justifikasinya terhadap “judicial review”, namun hal tersebut secara implisit sudah tercakup di dalam teorinya mengenai ketergantungan timbal balik dari tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan legislatif (reciprocal dependence of three powers). Prinsip kemanfaatan (the principe of utility) menekankan jangan sampai terjadi perampasan dalam bentuk apapun terhadap kekuasaan legislatif.[27]
Salah satu hal penting yang perlu dicatat mengenai pendekatan utilitarianisme terhadap konsep keadilan adalah Bentham tidak membahas keadilan secara sistematis dan detail. Teori Bentham mengenai keadilan sebetulnya didasarkan kepada kebahagiaan individual, bukan kebahagiaan komunal (masyarakat). Namun Bentham tidak pernah mau mengakuinya. Meskipun diakui teori keadilan Bentham kurang komplit dan memuaskan, namun pendekatan utilitarianisme mengenai keadilan diakui sebagai tonggak penting dalam evolusi teori keadilan. Nilai kontribusinya terletak pada upaya rasional dengan pendekatan analitik dalam mewujudkan kebenaran dan realitas yang membuka jalan bagi pembaharuan masyarakat meskipun disadari adanya kelemahan dalam konsep tersebut. Kontribusi terbesar pendekatan utilitarianisme terhadap konsep keadilan adalah utilitarianisme memisahkan keadilan dari teologi, mistisisme, imaginasi dan spekulasi yang mengarah kepada ilusi kekhawatiran dan kefrustasian.
- Hukum, Kebebasan, dan Pemerintahan
Gagasan Bentham mengenai kebebasan adalah apa yang sekarang dikenal sebagai “kebebasan negatif” (negative liberty), yaitu kebebasan dari belenggu dan paksaan eksternal. Menurut Bentham, kebebasan adalah bebas dari kekangan (the absence of restraint). Dengan pengertian ini, maka seseorang yang tidak mendapat gangguan dari pihak lain, maka dia telah mendapatkan kebebasannya. Bentham menolak bahwa kebebasan itu bersifat alamiah atau ada lingkup kebebasan sebelumnya dimana seorang individu dianggap berdaulat. Dia mengklaim bahwa manusia senantiasa hidup di masyarakat dan oleh karenanya tidak ada yang disebut sebagai sesuatu yang alamiah (meskipun demikian Bentham membedakan antara “political society” dan “natural society”), juga tidak ada yang namanya kontrak sosial (satu gagasan yang menurut Bentham bukan saja bersifat a historis tapi juga merusak). Meskipun demikian, dia mencatat bahwa terdapat perbedaan penting antara ruang publik dan ruang privat yang secara moral memiliki konsekuensi penting. Selain itu Bentham juga berpendapat bahwa kebebasan itu adalah sesuatu yang baik meskipun bukan merupakan sesuatu yang bernilai fundamental, karena ia merefleksikan prinsip “the greatest happiness”.
Atas dasar gagasan kebebasan yang diusungnya, Bentham sebagaimana Hobbes, menganggap hukum sebagai sesuatu yang bersifat “negatif”. Dengan mengacu kepada idea mengenai kebahagiaan (pleasure) dan ketidaksenangan (pain), maka kebebasan adalah sesuatu yang baik (pleasant) dan konsekuensinya maka pembatasan terhadap kebebasan adalah sesuatu yang buruk (painful). Hukum yang karakteristik utamanya adalah bersifat pembatasan terhadap kebebasan dan menyakitkan bagi mereka yang kebebasannya terrenggut, secara prima facie, hukum adalah sesuatu yang buruk (evil). Tapi, Bentham mengakui bahwa hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban sosial dan juga untuk menghadirkan pemerintahan yang baik. Sebagaimana Locke, Bentham mengakui peran positif hukum untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.
Berbeda dengan para pemikir pendahulunya, Bentham berpendapat bahwa hukum tidak berakar pada hukum alam (natural law), melainkan suatu perintah yang merupakan ekspresi kehendak dari pihak yang berkuasa. Paham ini yang kemudian dikembangkan oleh John Austin dan masyhur dikenal sebagai madzhab positivisme. Secara demikian, suatu hukum yang berwujud perintah yang secara moral dipertanyakan atau secara moral dikualifikasikan sebagai perbuatan jahat, atau yang tidak didasarkan atas persetujuan (consent), tetap merupakan hukum. Intinya hukum adalah perintah (command). Perintah adalah senjatanya penguasa (pemerintah).
- Hak
Pandangan Bentham mengenai hak akan dapat di pahami dalam konteks serangan Bentham terhadap konsep hak-hak alamiah (natural rights). Kritik Bentham mengenai hal ini dapat dibaca secara lengkap dalam salah satu karyanya Anarchical Fallacies yang ditulis pada tahun 1791-1795, namun baru diterbitkan pada tahun 1816 di Prancis. Hak, menurut Bentham, adalah sesuatu yang diciptakan atau dilahirkan oleh hukum dan hukum itu sendiri tidak lain adalah perintah penguasa. Oleh karenanya, keberadaan hukum dan hak-hak lainnya memerlukan adanya pemerintah. Hak yang meskipun tidak selalu berhubungan dengan kewajiban yang ditentukan oleh hukum, sebagaimana juga kata Hobbes, adalah sesuatu yang secara eksplisit diberikan oleh hukum kepada kita atau sesuatu yang secara implisit ada di dalam hukum. Bentham menolak pandangan yang mengatakan bahwa ada hak yang tidak didasarkan kepada perintah penguasa atau yang ada sebelum terbentuknya pemerintahan.
Menurut Bentham, terma “natural right” adalah pemutarbalikkan bahasa yang bersifat ambigu, sentimentil, dan figuratif (kiasan) dan potensial melahirkan pemahaman yang anarkhis. Terma “natural right” dianggap sebagai ambigu, karena terdapat hak-hak umum, yaitu hak yang tidak terkait dengan objek tertentu, sehingga seseorang dapat mengklaim apapun yang mereka mau. Akibat dari pelaksanaan hak alamiah universal (universal natural right) akan menyebabkan hilangnya hak secara keseluruhan, karena apa yang merupakan hak setiap orang akhirnya menyebabkan tidak ada hak perorangan sama sekali. Tidak ada sistem hukum yang dapat berfungsi dengan konsepsi tentang hak yang sangat luas seperti ini.
Terma “natural right” juga bersifat figuratif, karena menurut Bentham sebenarnya tidak ada hak yang lahir sebelum adanya pemerintah. Asumsi adanya hak sebelum ada pemerintah tampaknya didasarkan kepada teori kontrak sosial. Berdasarkan teori ini, individu-individu membentuk masyarakat dan memilih pemerintah melalui penghilangan hak-hak tertentu yang dimiliki mereka. Tapi sebagaimana telah dikatakan Bentham, teori kontrak sosial hanyalah sebuah fiksi dan a historis. Pemerintah lahir karena kebiasaan atau dengan kekuatan, sedangkan suatu kontrak atau perjanjian agar mengikat mensyaratkan harus adanya pemerintah untuk memaksa agar kontrak tersebut berlaku mengikat.
Idea tentang “natural right” dianggap anarkhis, karena hak alamiah ini memerlukan kebebasan dari semua pengekangan khususnya dari pengekangan hukum. Hak alamiah hadir sebelum adanya hukum, oleh karenanya ia tidak dapat dibatasi oleh hukum. Dengan pengertian seperti ini, karena setiap orang memiliki kebebasan dan kebebasan itu tidak bisa dibatasi oleh hukum karena hadir sebelum adanya hukum, maka hasilnya adalah anarkhi, demikian kata Bentham. Untuk mendapatkan hak dalam makna yang sebenarnya mensyaratkan bahwa pihak lain tidak boleh melakukan intervensi terhadap hak-hak seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa hak adalah sesuatu yang harus dapat diwujudkan. Hal ini akan terkait dengan keperluan adanya pembatasan, dan pembatasan itu adalah wilayahnya hukum.
Akhirnya Bentham menyimpulkan bahwa terma “natural right” tidak lain hanyalah terma yang “nonsense”. Hak yang menurut Bentham harus merupakan sesuatu yang berwujud (real rights), tidak lain adalah hak yang diberikan oleh hukum (legal rights). Setiap hak harus berdasarkan hukum dan bersifat spesifik (baik objek maupun subjeknya). Hak harus dibuat karena kondusivitas dan korelativitasnya terhadap kebahagiaan masyarakat. Misalnya, karena alasan untuk kepentingan masyarakat, suatu hak harus dihapuskan, maka hak tersebut dapat dihapus. Hal ini bisa dilakukan apabila hak tersebut terjamin adanya secara hukum. Sepanjang terjamin secara hukum, hak akan terlindungi keberadaanya, kalau tidak, maka hak tersebut hanyalah harapan kosong.
- Kelebihan dan Kelemahan
Banyak kritik dialamatkan kepada utilitarianisme Bentham terutama mengenai konsep pleasure and pain. Pemikiran Bentham mengenai pleasure and pain dinilai mereduksi manusia hanya sebagai makhluk pengindera semata (sensing creature). John Stuart Mill proponen utilitarianisme mengakui adanya dilema ini dan dia mencoba menawarkan jalan keluar dengan konsepnya yang ia sebut sebagai eudaimonistic utilitarianism. Disebut demikian, karena Mill membedakan kebahagiaan menjadi dua yaitu kebahagiaan tinggi dan kebahagiaan rendah. Kebahagiaan tinggi yang dalam bahasa Yunani disebut dengan eudaimonistic mencakup ilmu pengetahuan, hubungan sosial, budaya, dan kapasitas intelektual. Sedangkan kebahagian rendah mirip dengan yang dikonsepsikan oleh Bentham yang meliputi antara lain makan, minum, dan sensualitas.[28] Namun, pandangan ini masih tetap kontroversial, karena kebahagian tinggi itu hanyalah sesuatu yang diinginkan. Mill mencoba membela dengan mengatakan bahwa lebih baik menjadi manusia yang kurang bahagia daripada menjadi seekor babi yang bahagia. Lebih baik menjadi seorang Socrates yang kurang bahagia daripada menjadi seorang bodoh yang bahagia.[29]
Utilitarianisme Bentham berbeda dengan Mill, yang pertama dikenal dengan act– utilitarianism sedangkan yang kedua disebut rule-utilitarianism. Menurut Bentham, dalam setiap situasi moral, semua tindakan yang dapat menghasilkan sejumlah kebaikan harus tetap dilakukan tanpa memperhatikan sarananya. Act-utilitarianism membolehkan untuk mengabaikan hak dan aturan umum sepanjang tindakan yang tidak patut tersebut misalnya berdusta, dapat mengantarkan kepada tujuan yang baik. Namun, apabila setiap orang adalah seorang act-utilitarianism, maka sangat mungkin perbuatan bohong akan menjadi sesuatu yang biasa dan nilai-nilai kejujuran pada akhirnya akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan. Sebaliknya, menurut rule-utilitarianism bahwa aturan moral dan masyarakat dapat diikuti sepanjang kebahagiaan yang dihasilkannya sama baiknya dengan tindakan yang dilakukan dengan melanggar hukum. Aturan moral pada akhirnya harus berkontribusi bagi tercapinya seluruh kebaikan. David Brink menyimpulkan perbedaan keduanya sebagai berikut: “Act utilitarianism must condemn following rules when doing so is sub-optimal; rule utilitarianism need not.”[30]
Ungkapan sarkastik berikut menggambarkan secara jelas kelebihan dan sekaligus kelemahan utilitarianisme: the best of theories and the worst of theories. Utilitarianisme menjelaskan secara detail mengenai baik dan buruk suatu perbuatan dan juga konsekuensinya, namun melupakan bagian esensial dari moralitas yaitu keadilan. Teori ini mengabaikan bagaimana kebaikan itu didistribusikan, yaitu keadilan. Secara lebih spesifik, beberapa kelemahan sekaligus kritik terhadap utilitarianisme antara lain bagaimana cara mengetahui bahwa kebahagiaan dan kepuasan lebih mudah diukur secara kuantitatif daripada sebuah impian atau cita-cita. Paling tidak ada dua isu yang mengemuka. Pertama, apakah segala sesuatu dapat diukur secara kuantitatif? Beberapa hal tidak mudah untuk diukur misalnya cinta dan kebahagiaan keluarga, sementara yang lain mudah untuk diukur misalnya produktivitas dan yang bersifat fisik material. Kedua, apakah setiap barang atau materi yang bisa diukur memiliki nilai yang sepadan. Misalnya, apakah nilai kebahagiaan dari makan malam sepadan dengan kenikmatan tidur nyenyak? Utilitarianisme mengklaim bahwa kita bertanggung jawab atas semua pilihan kita. Persoalannya adalah apakah kita harus bertanggung atas pilihan orang lain yang mendatangkan akibat tertentu kepada kita. Bagi utilitarianisme, konsekuensi atau akibat lebih penting daripada motif sebuah perbuatan. Namun praktik menunjukkan sebaliknya, untuk sebuah hasil atau akibat dari suatu perbuatan ternyata didorong oleh motif yang berbeda. Pertanyaan penting lainnya adalah, siapa yang menghitung kepuasaan atau kebahagiaan itu? Dengan pendekatan utilitarianisme, kebahagiaan akhirnya akan tergantung kepada siapa yang menghitung. Seorang pemimpin perusahaan akan menghitung kebahagiaan karyawannya dari perspektif dia, bukan dari perspektif karyawannya. Perhitungan seperti ini akan jauh dari rasa keadilan.
Beberapa kelebihan utilitarianisme antara lain memiliki konsep nilai yang sederhana dan mendasar misalnya; moralitas sekuler, pendekatan akal sehat, egalitarianisme, fokus kepada kesejahteraan, dan penekanannya kepada hasil. Karena lebih menekankan kepada konsekuensi daripada motif suatu perbuatan, utilitarianisme dianggap memberikan kontribusi besar terhadap penggunaan analisis untung rugi (cost-benefit analysis) dalam pengambilan keputusan dan juga analisis kebijakan publik. Utilitarianisme juga dianggap memiliki prinsip-prinsip yang mampu menjawab setiap persoalan yang timbul. Teori ini juga dianggap bukan sekedar suatu sistem formal, melainkan substansi moral yang fokus kepada peningkatan kebahagiaan manusia dan pengurangan ketidakbahagiaan.
[1] Ruth Borchard, John Stuart Mill: The Man, Watts, London, 1957, hlm. 12.
[2] David Lyons, In the Interest of the Governed: A Study in Bentham’s Philosophy of Utility and Law, Clarendon Press, Oxford, 2003, hlm. 5.
[3] Encyclopaedia Britannica, Vol. 3, William Benthon Publisher, Chicago, 1965, hlm. 485.
[4] Lyons, Ibid, hlm. 5.
[5] Encyclopaedia Britannica, Loc.cit.
[6] Ibid. hlm. 486. Lyons, Op.cit., hlm. 6.
[7] Nina Rosenstand, The Moral of The Story: An Introduction to Ethics, McGraw-Hill, New York, 2005, hlm. 216.
[8] Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Kitchener, Batoche Books, 2000, hlm. 14.
[9] Ibid. By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness, (all this in the present case comes to the same thing) or (what comes again to the same thing) to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party whose interest is considered: if that party be the community in general, then the happiness of the community: if a particular individual, then the happiness of that individual.
[10] Axioma fundamental ini muncul pertama kali dalam karya Bentham yang berjudul “A Fragment on Government” pada tahun 1776, lihat J.H.Burns and H.L.A. Hart (eds.), A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government, The Collected Works of Jeremy Bentham, The Athlone Press, London, 1977, p. 393. Lihat juga Lyons, Op.cit., hlm. 12.
[11] Burns and Hart, Ibid., hlm. 173-174.
[12] Bentham, Op.cit., hlm. 31-32.
[13] Ibid.
[14] John Stuart Mill, On Liberty, Himmelfarb (ed.), Penguin Classics, London, 1974, hlm. 46.
[15] Bentham, Op.cit., hlm. 8.
[16] Lihat juga Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum: Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm 159.
[17] Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 59
[18] H.L.A. Hart, Essays on Bentham, Jurisprudence and Political Theory, Clarendon Press,
Oxford, 1982, hlm. 51
[19] John S. Mill, Utilitarianism, New York, 1957, hlm.63
[20] Ibid., hlm. 65.
[21] Ibid., hlm. 73, 78.
[22] Jeremy Bentham, (Charles Kay Ogden,ed.), Theory of Legislation F.B.Rothman, 1931, hlm. 94.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Upendra Baxi, Bentham’s Theory of Legislation, Tripathi, 1986, hlm. xxiv
[26] Lawrance C. Wanless, Gettel History of Thought, London, 1950, hlm. 313.
[27] Baxi, Op.cit., hlm. xxv.
[28] Brendan Sweetman, “Mill’s Utilitarianism,” Paper, Rockhurst University, Kansas City, 20 April 2015, hlm. 15.
[29] David O. Brink, Mill’s Progressive Principles, Oxford University Press, Oxford, 2013, hlm. 51.
[30] Ibid., hlm. 81.